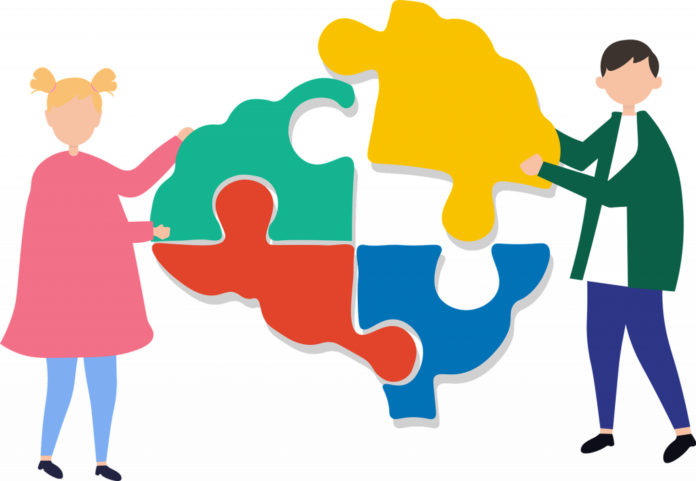
HIDUPKATOLIK.COM – Pagi tampak cerah dibasuh oleh cahaya surya. Aku bergegas menuju tempat kerjaku, sebuah pusat pelatihan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autisme. Tidak seperti biasa, pagi ini ada selumbar enggan menyusup bilik dadaku. Hari ini, aku harus memberikan terapi mengontrol emosi kepada beberapa siswa autis. Salah satunya, Bunga.
Aku sudah separuh menyerah menghadapi bocah berparas cantik itu. Emosinya mudah meletup. Tak jarang kesabaranku tiarap menghadapinya. Aku telah menggali berbagai informasi tentang Bunga. Alkisah, ibunya telah tiada sedari ia balita. Sedangkan ayahnya tergilas oleh kesibukan kerja. Waktu bersama Bunga tersisa sejumput. Sehari-hari, ia didampingi oleh perawat yang bolak-balik ganti.
“Apa Bunga sering mengamuk di rumah, Mbak?” tanyaku kepada perawat yang mengantarnya terapi.
“Ngamuk, Bu. Mesti super sabar mengurusnya,” ungkap si perawat seraya melepas setangkup senyum kecut, seakan ada kepenatan menibani hatinya.
Pagi itu, aku menerapkan terapi mengontrol emosi pada Bunga. Aku dan dia duduk berhadapan di satu meja. Kuletakkan sebuah mainan berbentuk harimau di dekatnya. “Ayo, Bunga, serahkan harimau ini ke tangan Ibu ya,” pintaku dengan suara selembut mungkin. Seketika Bunga melempar mainan itu hingga melesat cukup jauh dari meja. Ketika aku mengulangi terapi ini, dengan emosi, ia kembali membuang mainan tersebut.
Sementara mainan itu kuambil, sekali lagi aku mengatakan, “Jangan dilempar ya Sayang. Berikan harimau ini ke tangan Ibu ya…” Ternyata, secara tak terduga, bunga melempar mainan harimau itu ke wajahku. Aku terhenyak. Sebaris memar berjejak di pelipisku. Aku segera berlari, mencari obat merah untuk lukaku. Proses belajar-mengajar sontak kupungkasi. Seketika semangatku luruh.
Padahal, saat pertama kali datang ke pusat pelatihan ini, aku melihat segunduk tantangan teronggok di hadapanku. Tantangan itu menyulut idealismeku. Ternyata, kondisi saat ini terjungkir. Sumbu harapan yang bernyala di dadaku, mulai berkebit seperti kehabisan daya.
***
Autisme adalah gangguan pada sistem pusat otak anak yang menyebabkan terjadinya berbagai gangguan dan keterlambatan pada aspek tumbuh kembang anak, yakni sensori, motorik, kognitif, komunikasi, kontrol emosi, kemandirian, sosialisasi, interaksi, bahasa, dan perilaku. Pada hakikatnya, autisme adalah sebuah gangguan, bukan penyakit.
Intervensi terapi bagi penyandang autisme bukanlah untuk menyembuhkan (karena bukan penyakit), tetapi untuk membantu mendongkrak kemampuannya pada kesepuluh aspek tumbuh kembang yang terganggu. Penelitian menunjukkan bahwa yang terpenting adalah komitmen, konsistensi, dan keberlangsungan program terapi.
Masalah autisme pernah memikatku hingga aku memilih menjadi terapisnya. Aku pernah terpana menyaksikan seorang ibu yang kewalahan meredam emosi putranya yang menyandang autis, yang tantrum di sebuah selasar mal. Sekian pasang mata di sekitar lokasi sontak menatap keheranan. Namun, perempuan itu tak menggubrisnya akibat dilabrak oleh kesulitan menenangkan anaknya.
Iba menelusuk hatiku. Benakku mengelana, membayangkan kesulitan-kesulitan yang mencengkeram keseharian perempuan itu. “Apakah kondisi demikian tidak bisa diminimalisir?” pikirku. Aku percaya, setiap orang menyangga kesulitannya masing-masing. Kubayangkan, salib yang disangga oleh orang tua penyandang autis relatif tidak ringan.
Tiba-tiba, niatku menggeliat ingin mendulang keterampilan di seputar pendampingan bocah-bocah autis. Hingga akhirnya, aku menjadi terapis di sebuah pusat terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. “Aku ingin bekerja di situ,” ungkapku kepada ibuku. Aku menyadari, keteguhan hasratku, membuat ibu mengupayakan dana demi cita-citaku. Sedari aku masih remaja, ibulah penggerak ekonomi keluarga karena ayahku sakit-sakitan.
Ternyata, tidak mudah menjaga nyala semangat yang semula berkobar. Ada saja kendala yang melintang di depanku, terutama dalam hal kesabaran. Di tempat ini, aku memergoki kesabaranku terbilang landai dibandingkan terapis lain. Terlebih, jika anak-anak mengamuk. Berbagai insiden mewarnai, memunculkan risiko tersendiri. Kekesalan pun kian tanak di hatiku menghadapi ulah para siswa.
Hal ini berpuncak pada peristiwa Bunga melukai pelipisku. Dalam bimbang, benakku menimbang apakah aku mampu bertahan. “Sampai kapan aku sanggup mendampingi mereka?”
***
Malam telah larut. Rembulan telah undur diri, sementara bintang-bintang mulai letih berkerlip di ubun-ubun langit. Saat itu, kelopak mataku nyaris terkatup. Kulit wajahku pun telah terlipat di antara kerutan sarung bantal. Tiba-tiba, ponselku bersuara dalam keheningan. Ada teks menyelonong di WhatsApp-ku.
“Waaah, aku lupa mematikan HP,” gerutuku. Entah mengapa, aku malah tergoda untuk membuka ponsel. “Huh, siapa malam begini masih mengirim teks,” kataku mendadak penasaran.
“Selamat malam. Saya, Ricky, papa Bunga,” sapa pengirim teks itu.
Aku terkesiap membacanya. Kubuka Profil Picture-nya. “Hmmm… gagah juga,” batinku.
“Selamat malam, Pak Ricky,” balasku seraya menepis kantuk.
“Mohon maaf atas insiden yang dilakukan Bunga tadi siang, Bu Maria.” Begitu isi teks berikutnya.
“Tidak apa, Pak,” tulisku lagi, basa-basi.
“Kalau mungkin, besok saya ingin berjumpa dengan Bu Maria untuk membicarakan soal Bunga,” lanjutnya.
“Baik, Pak. Besok kita bicarakan lagi,” sambutku.
Malam itu, sesabit senyum mengiringi lelapku.
Keesokan harinya, selepas waktu mengajar, Pak Ricky menjumpaiku. Pertemuan itu diwarnai dengan perbincangan tentang Bunga. Saat itu pula, empatiku mulai bertunas mendengarkan kisahnya.
Senja menyisakan sepotong matahari dengan warna laksana bara tatkala kami menyudahi pertemuan. Ada kesan yang tergurat tentang sosok ayah Bunga. Di balik pergulatan hidupnya, canda tawa mewarnai hingga keakraban mudah terpilin antara aku dan dia.
Tak kunyana, pertemuan pertama itu bakal disusul dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bila pada awalnya, kami berjumpa saat makan siang, berikutnya pertemuan dirancang untuk santap malam.
“Sekarang, kau kembali bersemangat mengajar anak-anak autis ya,” goda Dona, sejawat sekaligus sahabatku, sembari tergelak.
Selepas enam purnama, Papa Bunga mengusung kejutan untukku. Di bawah cahaya lilin tatkala bersantap malam, ia meminangku. “Maukah kau menjadi Mama Bunga?” Detak jantungku nyaris berhenti mendengarnya. Tepercik tanya di hatiku, “Secepat itukah?” Bisa jadi lelaki ini tak ingin menggantung keraguanku akan kehadirannya yang mendadak bertubi dalam hidupku.
Tentu tidak serta-merta aku menjawabnya. Ia sanggup membaca kegelisahanku. Ia mempersilakan aku mengurai nalar; bukan semata untuk mencintai sosoknya tetapi juga Bunga… Hmmm… siapa bilang cinta tidak bisa logis? Bukankah cinta sanggup merambah dimensi angka dan rasa sekaligus?
“Semoga Bunga tidak melemparku dengan piring ya kalau tahu aku akan menjadi mamanya,” candaku mencairkan kebekuan yang tiba-tiba menyeruak. Sementara telapak tanganku dingin dan bergetar. Dekapan Papa Bunga seketika menenangkan gejolak perasaanku yang mendadak rusuh.
Kini, ruang hatiku tak lagi kosong. Ayah seorang bocah autis siap menghuninya. Telah kuserahkan kunci ruang itu kepadanya.

Oleh Maria Etty
Majalah HIDUP, Edisi No.03, Tahun Ke-78, Minggu,21 Januari 2024


